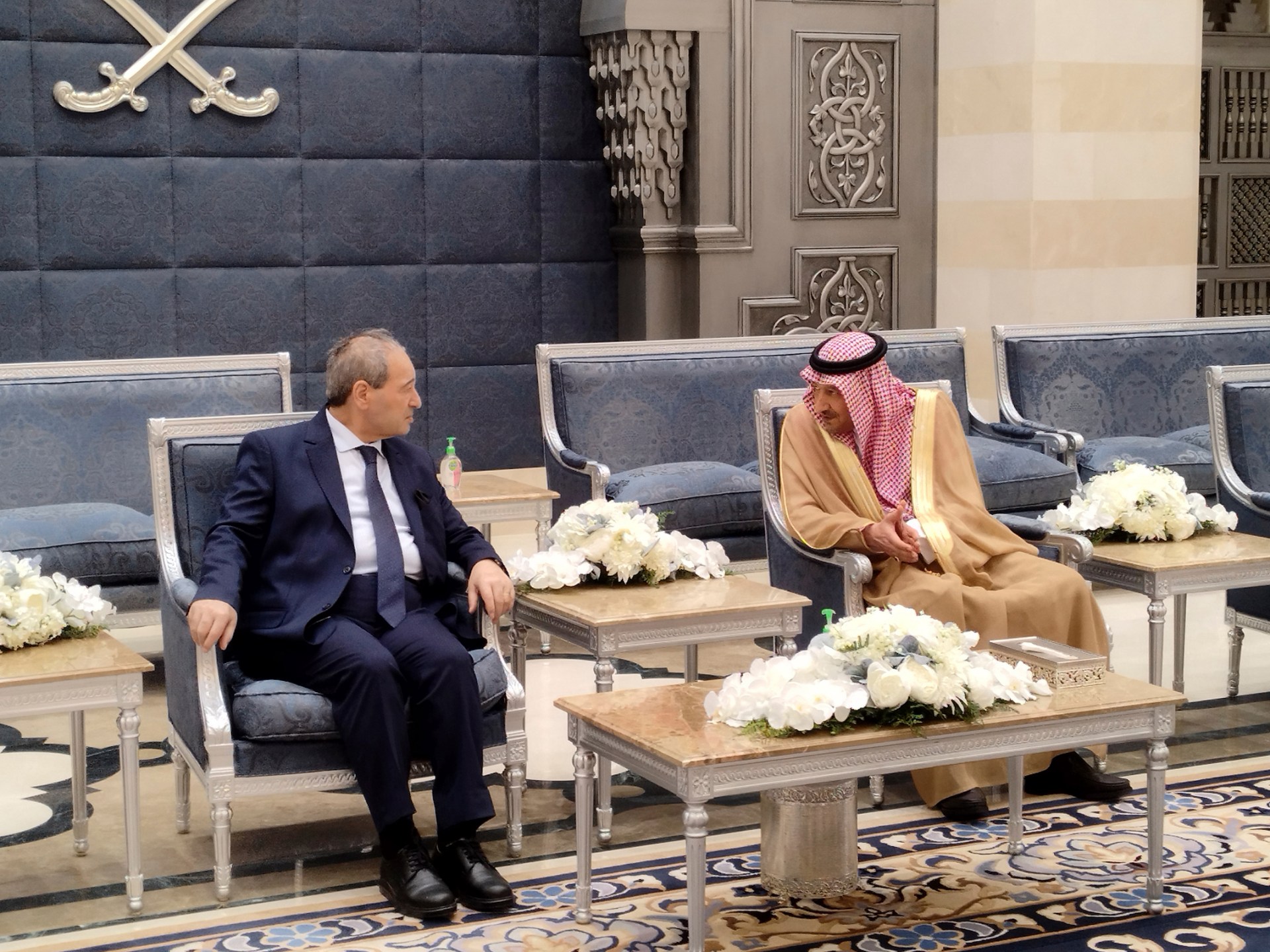Dua puluh tahun telah berlalu sejak invasi pimpinan AS ke Irak menggulingkan kediktatoran Saddam Hussein. Kelas politik yang merebut kekuasaan di Irak dengan janji menghapus otoritarianisme rezim Baath dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi telah gagal melakukannya.
Nyatanya, ia menggunakan taktik represif yang sama yang digunakan oleh Saddam untuk melindungi sistem pembagian kekuasaan etno-sektarian, yang dikenal sebagai “muhasasa ta’ifia”, yang didirikan setelah tahun 2003 dan melindungi kepentingan politik dan ekonominya yang sempit.
Tantangan terbesar untuk sistem ini datang pada tahun 2019 ketika rakyat Irak turun ke jalan secara massal untuk menuntut perubahan politik dan ekonomi yang mencerminkan janji yang dibuat kepada mereka pada tahun 2000-an. Reaksi kelas politik tanpa ampun. Ini melepaskan gelombang kekerasan yang mematikan dan, di bawah pemerintahan saat ini, telah berusaha menggunakan semua cara hukum dan legislatif untuk lebih memperkuat cengkeramannya yang menindas kekuasaan dan menghancurkan perbedaan pendapat.
Irak berjuang untuk memiliki suara
Invasi pimpinan AS ke Irak didasarkan pada gagasan bahwa penggulingan Saddam akan memungkinkan demokrasi berkembang dan hak asasi manusia dan sipil ditegakkan. Namun bahkan tahun 2005 Konstitusiditulis oleh politisi Irak yang diasingkan dan sekutu asing yang membuat janji-janji ini mengandung kata-kata yang tidak jelas, memungkinkan penyalahgunaan hak-hak sipil dengan mudah.
Misalnya, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi hanya jika tidak melanggar “moralitas” atau “ketertiban umum”. Ini, tentu saja, memungkinkan penggunaan ketentuan ini secara sewenang-wenang dan sembarangan untuk memberangus kritik media dan pemerintah Irak.
Pembungkaman suara-suara kritis seiring dengan penyebaran kekerasan politik telah memungkinkan elit politik Irak untuk memerintah sesuka hati dan memperkaya diri mereka sendiri di belakang rakyat Irak.
Tapi memperdagangkan satu penindas dengan yang lain bukanlah sesuatu yang mau diterima oleh rakyat Irak. Sudah pada tahun 2011 ketika seluruh Timur Tengah berada dalam kekacauan dan berusaha menyingkirkan kediktatoran dan penindasan, rakyat Irak turun ke jalan melawan kegagalan penguasa baru mereka untuk menyediakan layanan dasar dan standar hidup yang wajar.
Pada tahun-tahun berikutnya, protes terus berlanjut seiring dengan memburuknya situasi politik dan ekonomi di negara tersebut.
Pada Oktober 2019, bertahun-tahun kemarahan yang menumpuk meletus dalam protes massal di Irak tengah dan selatan. Ratusan ribu orang melakukan protes selama berminggu-minggu, menuntut tidak hanya kehidupan yang bermartabat, tetapi juga perbaikan sistem politik negara yang gagal. Protes juga mengangkat masalah kebebasan berbicara dan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran akan kepentingan kritis mereka.
Meskipun kekerasan mematikan dilancarkan terhadap protes oleh aktor negara dan non-negara, protes terus berlanjut. Solidaritas nasional yang mereka terima memberikan pukulan telak bagi elit politik, yang tumbuh subur dalam menyebarkan perpecahan dan mempertahankan budaya ketakutan. Itu juga menyebabkan pada tahun 2021 kekalahan elektoral dari partai-partai yang memicu kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.
Penindasan kebebasan berekspresi
Kekuatan politik yang dihukum oleh pemilih Irak dalam pemilihan parlemen terakhir karena korupsi dan partisipasi mereka dalam menekan protes 2019 kembali dengan pembalasan tahun lalu.
Mereka membentuk koalisi yang dikenal sebagai Kerangka Koordinasi Syiah, (SCF) dan setelah penarikan blok pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr dari parlemen, yang menerima jumlah suara terbanyak, mereka dapat memanfaatkan ketentuan konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan.
SCF bersekutu dengan partai-partai Sunni dan Partai Demokrat Kurdistan (KDP) untuk membentuk koalisi Administrasi Negara dan mengontrol parlemen. Sejak itu, kelompok tersebut telah meluncurkan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai “kontra-revolusi” terhadap pencapaian penting yang diperoleh setelah protes Oktober 2019.
Pemerintah yang dipimpin SCF memiliki membatasi ruang untuk kebebasan berbicara dan kritik. Pasal 225-227 KUHP yang sering digunakan oleh rezim Baath adalah digunakan menargetkan aktivis hak-hak sipil hanya karena mereka mengungkapkan pendapat mereka di media sosial atau tradisional. Mereka mengandung bahasa yang tidak jelas dan luas yang memungkinkan otoritas Irak untuk mengadili siapa saja yang menghina “pemerintah”, “pasukan militer” atau “lembaga semi-resmi” dan menghadapi hukuman tujuh tahun penjara.
Salah satu contoh penting tentang bagaimana pasal-pasal ini telah disalahgunakan baru-baru ini adalah kasus aktivis Haider al-Zaidi. Dia dihukum pada bulan Desember hingga tiga tahun penjara karena tweet bahwa Abu Mahdi al-Muhandis, mendiang kepala Pasukan Mobilisasi Populer, yang pada Januari 2020 bersama dengan Qassem Soleimani, kepala Pasukan Quds di wilayah Islam Iran dalam serangan pesawat tak berawak AS adalah dibunuh, dikritik. Garda Revolusi Corp.
Pada bulan Maret, analis politik Mohammed Na’naa’ adalah ditangkap karena mengkritik Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, sementara jurnalis Qudus al-Samaraie dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena pencemaran nama baik setelah seorang perwira militer senior mengajukan gugatan terhadapnya. Ini hanyalah beberapa contoh dari semakin banyak tokoh publik yang dibungkam yang berani mengkritik elit politik dan status quo.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga didirikan sebuah komite untuk menghukum siapa pun yang memposting “konten cabul” secara online berdasarkan pasal 403 KUHP, yang terkait dengan istilah samar lainnya – “moral publik”. Sebagai akibat dari pasal ini, individu dapat dihukum hingga dua tahun penjara karena melanggar standar yang ditentukan semata-mata oleh pandangan subjektif kementerian tentang moralitas.
Pada bulan Februari ada lebih dari 10 orang ditangkap berdasarkan Pasal 403, termasuk influencer media sosial seperti Aboud Skaiba, yang kemudian dibebaskan setelah protes publik, dan Assal Hossam, yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
Dewan Mahkamah Agung, yang disebut badan hukum independen, baru-baru ini keluar dukungan dari Kementerian Dalam Negeriupaya baru-baru ini untuk mengadili individu karena “menghina institusi negara”.
Pembatasan partisipasi politik
Salah satu pencapaian terpenting yang dicapai oleh protes pada tahun 2019 adalah penerapan undang-undang pemilu yang baru. Hal ini memungkinkan kekuatan politik baru untuk mengorganisir dan menantang status quo, dan sebagai hasilnya sekitar 30 kandidat yang mewakili kelompok ini masuk parlemen.
Elit politik melihat ini sebagai ancaman terhadap monopoli kekuasaannya. Setelah SCF membentuk pemerintahan baru, SCF mendorong amandemen undang-undang pemilu, yang mengembalikan metode penghitungan suara elektoral. menguntungkan para pihak dari kelas politik yang mapan. Ada begitu banyak penentangan terhadap reformasi ini sehingga parlemen harus memberikan suara dalam semalam dan pasukan keamanan memecat anggota parlemen yang memprotesnya.
Dengan memberdayakan partai-partai etno-sektarian yang dominan, undang-undang yang diamandemen memperkuat sistem politik yang gagal saat ini dan melemahkan jalan demokrasi Irak. Itu juga bertentangan dengan identitas nasional bersama, di mana protes tahun 2019 berunjuk rasa.
Meski sudah 20 tahun sejak berakhirnya pemerintahan Saddam, jalan menuju demokrasi di Irak masih sulit dipahami. Namun, itu sangat layak untuk diperjuangkan. Meskipun mereka telah mengalami banyak kemunduran dan menghadapi musuh yang tangguh – kelas politik yang berpegang teguh pada kekuasaan dengan cara apa pun – warga Irak harus melanjutkan perjuangan mereka. Protes tahun 2019 dan keuntungan yang diperoleh – meskipun berumur pendek – menunjukkan jalannya.
Rakyat Irak harus terus mendorong hak-hak sipil seperti kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil dan akuntabilitas dan harus menjaga masalah ini di mata publik untuk bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang ingin mendirikan kediktatoran baru. Bahkan jika kemajuan berjalan lambat atau menemui hambatan, rakyat Irak tidak boleh kehilangan harapan. Perubahan itu mungkin dan tak terhindarkan. Dan kali ini bukan politisi ekspatriat Irak dan sekutu asing mereka yang memimpinnya, tetapi pemuda Irak dan aktivis masyarakat sipil.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi editorial Al Jazeera.